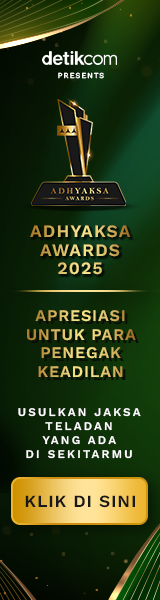BENGKALIS, Classnews.id – Di bangunan Huis Van Bewaring te Bengkalis atau Jell Belanda di jalan Pahlawan, kota Bengkalis kembali dijadikan pusat kegiatan pada hari ketiga dalam rangkaian ZAMARA 2025, Sabtu (22/11/25) malam.
Di hari ketiga ini, ZAMARA 2025 menampilkan Komedi Musikal Melayu, berjalan dalam ketegangan intelektual yang khas, dalam pembacaan makna tubuh pesisir, analisis sejarah zapin lintas Selat Melaka, dan diskusi kritis tentang ekonomi rumah tangga perempuan.
Namun, di tengah padatnya narasi akademik, dramaturgi tubuh, dan alur diskusi yang sesekali menegangkan, ada satu fragmen yang memecahkan suasana komedi musikal Melayu yang dibawakan oleh Mak Dara dan Lepok.
Seolah-olah, setelah satu jam menyimak teori, sejarah, dan peta kebudayaan, ruangan memerlukan sebuah “retak kecil”—dan komedi sleptik itu hadir menjadi pusat perhatian, mencuri dominasi panggung, dan mengubah ritme ruangan secara total.
Mak Dara dan Lepok tidak datang dengan kostum megah atau perangkat teatrikal berat; mereka hadir dengan bahasa tubuh yang cair, spontan, dan akrab—seolah dua sosok dari rumah sebelah yang tiba-tiba masuk dan berkata, “sudahlah, mari kita tertawa sebentar.”
Dan penonton pun tak kuasa menolak. Suara pertama yang keluar dari Mak Dara saja sudah membuat orang-orang menoleh, sementara gaya berlebih Lepok—antara malu-malu dan sengaja mengundang reaksi—menghadirkan tawa yang langsung menyebar seperti api kecil di alang-alang kering.
Komedi musikal itu dibalut dengan lagu-lagu Melayu yang sudah akrab di telinga orang pesisir: Nona Singapura, Raja Doli, Bujang Telajak, hingga sebuah lagu Randai Kuantan “Lontong Sate” yang membuat seluruh ruangan berguncang oleh tawa dan tepukan.
Ada saat di mana Mak Dara mengganti lirik sepersekian detik lebih cepat dari musiknya, dan Lepok masuk telat tetapi percaya diri—justru di titik-titik “ketidaksempurnaan” itu para penonton tertawa paling keras. Suatu jenis kegembiraan yang tidak dibuat-buat.
Ketika Mak Dara mengajak penonton berjoget pelan sambil menyanyikan Nona Singapura, beberapa tamu undangan yang sejak pagi menanggapi diskusi saintifik dengan wajah serius tiba-tiba ikut menggoyang bahu. Pada lagu Bujang Telajak, Mak Dara meminta salah satu bapak-bapak maju ke depan, dan seluruh ruangan pecah oleh tawa ketika si bapak dengan malu-malu mencoba mengikuti gerak sederhana namun nakal itu.
Tidak lama kemudian, ketika Lepok menyanyikan “Lontong Sate”—dengan dialog bertingkat yang memparodikan gaya pantun—gigi geraham sebagian besar penonton tampak jelas karena tawa mereka yang tak tertahan.
Namun, di balik semua keriuhan itu, ada sesuatu yang lebih jauh daripada sekadar hiburan. Komedi musikal tersebut tidak memperolok; ia memotret. Ia tidak menyepelekan; ia menyingkap. Mak Dara dan Lepok menertawakan kegugupan masyarakat, menertawakan relasi kuasa kecil di rumah tangga, menertawakan posisi gender yang cair tetapi seringkali dipaksa kaku, menertawakan tradisi, modernitas, dan ketidaktepatan kita dalam membaca zaman.
Dengan kata lain, mereka menertawakan kita—tapi bukan dengan cara merendahkan. Mereka mengajak kita menyadari bahwa tawa adalah satu-satunya ruang aman untuk membicarakan hal-hal yang sering tidak enak diucapkan secara langsung.
Di akhir pertunjukan, ketika tawa perlahan mereda dan lampu kembali stabil, suasana yang semula riuh berubah menjadi ruang hening yang penuh jeda. Dalam jeda itulah muncul satu pertanyaan yang seolah berputar di udara, menyentuh siapa saja yang hadir:
Apa sebenarnya yang sedang kita tertawakan? Apakah kita sedang menertawakan negeri ini dengan segala ketidakteraturan ? Atau kebiasaan-kebiasaan kecil yang diam-diam kita tahu tidak lagi selaras dengan zaman?
Mungkin kita sedang menertawakan ketidakmampuan kita sendiri untuk jujur melihat kenyataan, atau menertawakan diri kita yang terlalu sering merasa semuanya baik-baik saja padahal tidak demikian. Pertanyaan itu menggantung—bukan untuk dijawab saat itu juga, tetapi untuk dibawa pulang dalam kepala, sebagai ajakan untuk membaca situasi dengan mata yang lebih lebar dan hati yang lebih waspada.
Komedi itu, pada akhirnya, tidak berdiri sebagai selingan. Ia menjadi cermin. Sebuah jendela kecil yang memperlihatkan realitas bahwa di balik gelak tawa, ada kehidupan yang kompleks—politik keseharian, ekonomi kecil rumah tangga, relasi gender, dan dinamika budaya yang bergerak tetapi tidak selalu harmonis.
Tawa itu menghangatkan suasana, tetapi juga mengingatkan kita bahwa panggung yang dibangun dengan imajinasi perdamaian semata-mata seringkali hanya menutupi kegentingan di bawahnya. Maka, kita membutuhkan tidak hanya panggung komedi, tetapi juga panggung intelektual; tidak hanya ruang hiburan, tetapi ruang pemikiran.
ZAMARA hari ketiga menunjukkan bahwa keduanya dapat berdiri berdampingan—dan justru karena itu, kita bisa menertawakan kenyataan tanpa kehilangan kesadaran untuk memperbaikinya.(***)